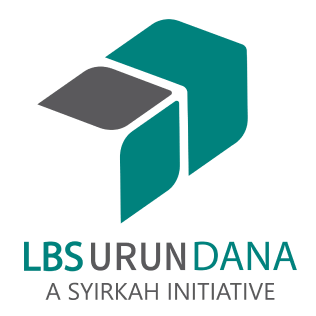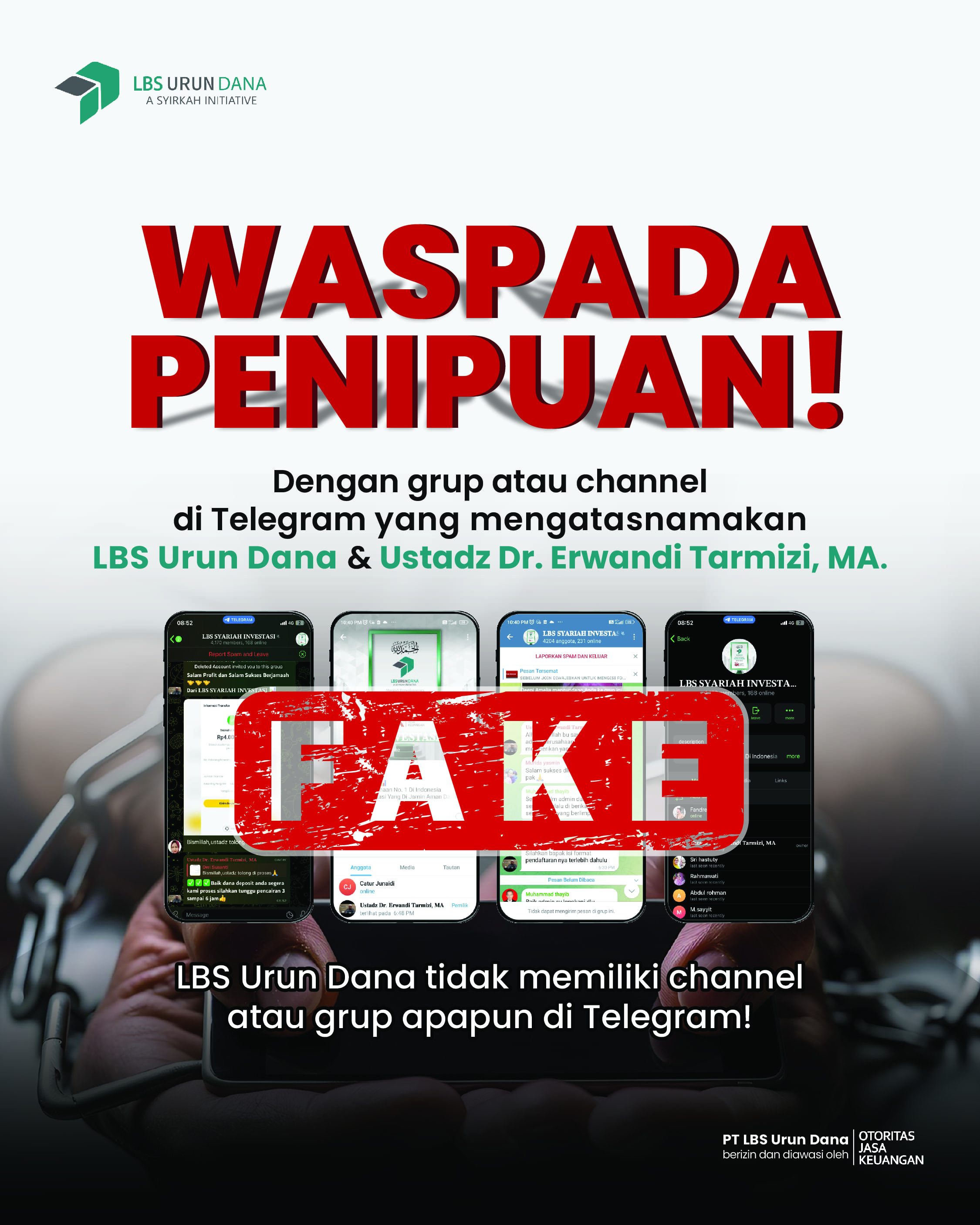artikel
23 Oktober 2025
Nah Loh! 4 Akad Kerja yang Diam-Diam Gharar, Gak Berkah Rugi Pula!
Dalam praktek dunia kerja, hubungan antara pemilik usaha dan pekerja tidak hanya diatur oleh kesepakatan lisan atau tertulis, tetapi juga oleh prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Salah satu prinsip penting dalam hal ini adalah larangan gharar, yaitu unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian atau pertikaian di antara pihak-pihak yang berakad.
Buku Harta Haram (2021) karya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA memberikan penjelasan rinci mengenai berbagai bentuk akad kerja yang berpotensi mengandung unsur gharar. Penjelasan ini penting dipahami agar hubungan kerja tetap sah secara syariah dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak, baik pemilik usaha maupun pekerja.
1. Gaji Pokok dan Bonus
Dalam dunia kerja modern, sistem gaji pokok ditambah bonus menjadi hal yang lazim digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Namun dalam praktiknya, besaran bonus sering kali tidak tetap, bisa lebih kecil, lebih besar, atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Ketidakpastian inilah yang menimbulkan unsur gharar, karena menyebabkan total gaji yang diterima karyawan menjadi tidak pasti.
Pertanyaannya, apakah ketidakjelasan ini dapat merusak akad kerja?
Dalam bukunya Ustadz Erwandi menjelaskan bahwa gharar hanya membatalkan akad jika terdapat pada bagian pokok akad (daar), bukan pada bagian tambahan atau pengikut (tabi’). Dalam sistem gaji pokok dan bonus, yang menjadi fokus akad adalah gaji pokok, sedangkan bonus hanyalah tambahan yang bersifat kondisional.
Maka dari itu, akad kerja tetap sah, dan sistem gaji seperti ini diperbolehkan karena tidak mengandung gharar yang merusak. Bahkan, sistem ini dinilai saling menguntungkan karena memberi ruang penghargaan atas kinerja pegawai.
2. Upah Berdasarkan Persentase Penjualan
Sistem upah berdasarkan persentase penjualan juga banyak diterapkan, terutama untuk posisi seperti tenaga penjualan (sales). Semakin tinggi volume penjualan yang dicapai, semakin besar pula upah yang diterima. Namun jika tidak ada penjualan, karyawan tidak mendapatkan upah. Dalam kondisi ini, besaran pendapatan karyawan tidak diketahui saat akad disepakati, sehingga unsur gharar muncul dengan jelas.
a. Pendapat Pertama
Mazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat bahwa sistem ini tidak sah, karena besarnya upah belum diketahui saat akad dibuat. Imam An-Nawawi mencontohkan, jika pemilik barang berkata kepada wakil penjual, “Jual barang ini dengan harga sekian, dan jika terjual, kamu mendapat satu persepuluh dari hasilnya”, maka akad tersebut tidak sah karena upahnya tidak pasti.
b. Pendapat Kedua
Mazhab Hanbali memiliki pandangan berbeda dan membolehkan sistem ini. Menurut mereka, upah telah jelas ditetapkan dalam bentuk persentase tertentu dari hasil penjualan. Akad semacam ini serupa dengan mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai persentase yang disepakati di awal. Pendapat ini dinilai lebih kuat karena mempertimbangkan kebutuhan praktis dan keadilan bagi kedua belah pihak.
Baca juga: Cengli! Kupas Tuntas Bagi Hasil dalam Islam, Cuan Halal Tanpa Drama Riba!
Sales yang rajin dan mampu menjual banyak produk akan memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada yang tidak aktif, sehingga sistem ini tetap adil meskipun terdapat unsur ketidakpastian.Dengan demikian, sistem upah berbasis persentase penjualan diperbolehkan, karena unsur gharar-nya bersifat ringan dan dibutuhkan dalam praktik ekonomi modern.
3. Upah Berdasarkan Besarnya Laba
Bentuk lain dari akad kerja yang mengandung unsur ketidakpastian adalah sistem bagi hasil antara pemilik kendaraan dan sopir. Misalnya, seorang sopir angkot memperoleh pendapatan harian sebesar Rp400.000, lalu Rp100.000 digunakan untuk biaya perawatan kendaraan dan sisanya dibagi dua antara sopir dan pemilik kendaraan. Jika pendapatan di bawah Rp100.000, seluruhnya digunakan untuk biaya operasional.
Dalam kasus ini, timbul pertanyaan apakah akad tersebut sah menurut hukum Islam?
a. Pendapat Pertama
Mazhab Hanafi dan Syafi’i menilai akad tersebut tidak sah. Jika dikategorikan sebagai akad mudharabah, maka modal harus berupa uang tunai, bukan barang seperti kendaraan. Sedangkan bila dianggap sebagai akad ijarah (sewa jasa), akad tersebut tetap mengandung gharar karena upah tidak jelas jumlahnya, bisa besar, kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali.
b. Pendapat Kedua
Mazhab Hanbali menyatakan bahwa akad seperti ini diperbolehkan. Meskipun tidak tergolong mudharabah maupun ijarah, akad ini mirip dengan musaqah, yaitu bentuk kerja sama di mana hasil dibagi sesuai kesepakatan. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar:
“Rasulullah ﷺ menyerahkan kebun kurma di Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka rawat, dengan perjanjian bahwa mereka mendapat setengah hasil panennya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Berdasarkan kaidah umum muamalah, setiap akad pada dasarnya boleh selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Maka dalam konteks ini, gharar yang ada tidak merusak akad karena bersifat ringan dan disepakati bersama.
4. Penetapan Upah Berdasarkan Sisa dari Harga yang Dipatok oleh Pemilik Barang
Model lain yang cukup sering ditemui adalah ketika pemilik barang mematok harga tertentu, lalu berkata kepada perantara, “Jual barang ini, dan jika terjual lebih dari harga yang ditetapkan, kelebihannya menjadi milikmu.” Contohnya dapat ditemukan dalam praktik jual beli mobil, tanah, atau rumah menggunakan jasa calo. Dalam sistem ini, calo memperoleh upah dari selisih antara harga yang dipatok pemilik dan harga jual kepada pembeli.
Bagaimana tinjauan syariat terhadap akad seperti ini?
a. Pendapat Pertama
Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan mayoritas ulama melarang sistem ini. Ibnu Rusyd menjelaskan, termasuk akad yang tidak diperbolehkan adalah ketika pemilik barang berkata, “Jual pakaian ini, jika terjual lebih dari sepuluh dirham, lebihnya menjadi hakmu.” Akad seperti ini dianggap tidak sah karena upah calo tidak jelas dan mengandung unsur gharar.
Baca juga: Awas Kegocek! Di Balik Diskon dan MLM Ada Gharar yang Mengintai!
b. Pendapat Kedua
Mazhab Hanbali, Ibnu Sirin, dan Ishaq bin Rahawaih membolehkan sistem ini. Dalilnya sebagai berikut:
1. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwa Ibnu Abbas berkata:
“Boleh hukumnya seseorang mengatakan: jual kain ini, jika terjual lebih dari harga sekian, maka lebihnya adalah upahmu.”
Tidak ada ulama yang menentang pernyataan ini, sehingga dipahami telah terjadi ijma sukuti yang membolehkannya. Artinya, gharar dalam kasus ini dikecualikan dari larangan umum.
2. Kasus ini juga dapat diqiyaskan dengan akad mudharabah, di mana upah pekerja (mudharib) bergantung pada besar kecilnya keuntungan, yang bisa besar, kecil, atau bahkan tidak ada sama sekali, tergantung hasil perniagaan.
Pendapat yang membolehkan dinilai lebih kuat karena sesuai dengan hukum asal muamalah yang memperbolehkan setiap akad selama tidak ada dalil yang melarang. Unsur gharar dalam akad ini termasuk kategori ringan dan dikecualikan berdasarkan ijma. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar akad ini tetap sah:
a. Calo harus mendapatkan izin atau perwakilan dari pemilik barang untuk menjualkan barang tersebut. Jika tidak ada perjanjian wakalah, maka transaksi yang dilakukan tidak sah.
b. Calo boleh menjual dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan jika hal tersebut disyaratkan sejak awal dalam akad. Namun, jika ia menjual dengan harga lebih tinggi tanpa kesepakatan, maka tindakan tersebut termasuk tidak amanah dan akadnya batal.
Baca juga: Naudzubillah! 7 Praktik Zalim yang Bikin Rezeki Anda Kabur Tanpa Disadari!
Keempat bentuk akad di atas menunjukkan bahwa tidak semua gharar membatalkan akad. Selama gharar hanya terdapat pada aspek tambahan, tidak menyentuh inti akad, dan ada kebutuhan mendesak dalam praktiknya, maka akad tersebut tetap sah. Prinsip utama dalam muamalah Islam adalah kemaslahatan bersama.
Selama akad dilakukan dengan ridha, kejujuran, dan kesepakatan yang jelas, maka insyaAllah hubungan kerja tersebut sah secara syariah dan mendatangkan keberkahan bagi kedua belah pihak. Wallahualam bissawab.